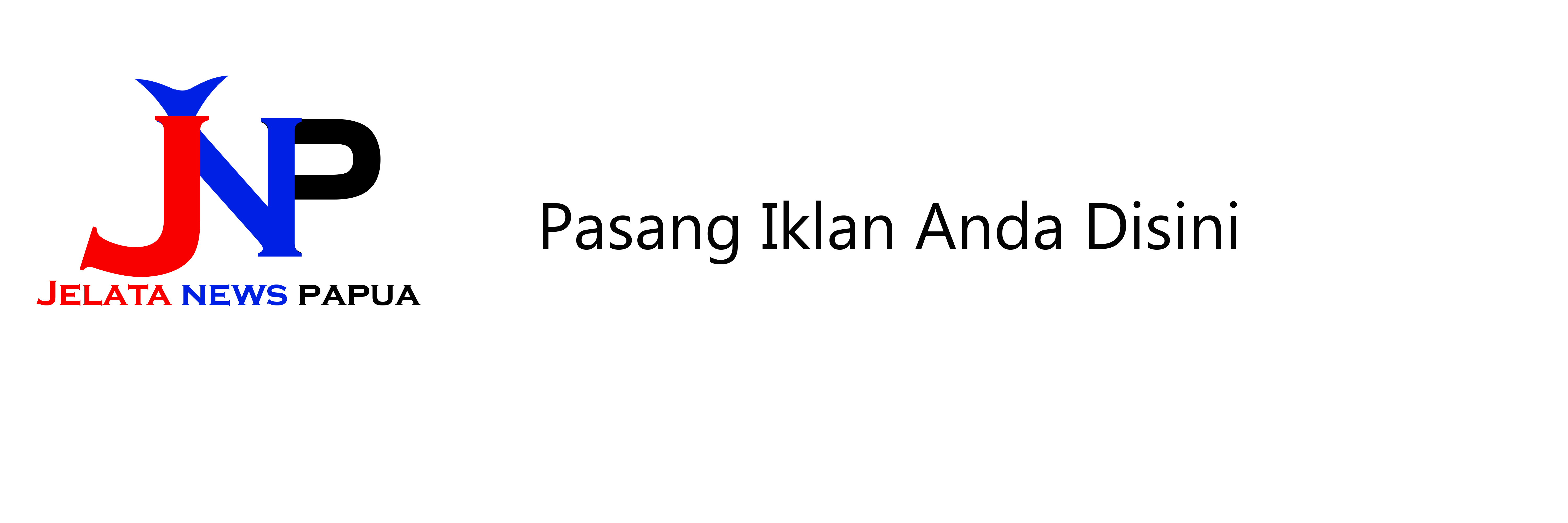Oleh Agustinus A. Dogomo*
Tanah yang dulu tenang kini jadi ladang kenangan luka. Sejak 1963, ketika bendera Bintang Kejora diturunkan dan digantikan Merah Putih, guncangan besar menggoyahkan akar-akar damai di tanah Papua. Sejak saat itu, langkah kaki rakyat Papua bukan lagi menuju pesta adat, melainkan pengungsian, pelarian dari senapan dan bayang-bayang rezim.
Jejak air mata menetes dari Pegunungan Tengah hingga pesisir Selatan. Pada tahun 1984, lebih dari 10.000 orang Papua melintasi batas negara menuju Papua Nugini, tepatnya ke daerah Black Wara. Mereka tidak membawa koper, hanya luka dan mimpi tentang rumah yang telah direnggut. Peristiwa ini menyusul pembunuhan budayawan Arnold Clemens Ap dan pembubaran grup musik Mambesak, simbol perlawanan kultural yang ditakuti penguasa (Human Rights Watch, 1984).
Di kamp-kamp pengungsian seperti Vanimo dan Kiunga, anak-anak tumbuh tanpa mengenal bangku sekolah. Mereka tahu arti kata “lari”, “sembunyi”, dan “diam saat malam tiba”. Di balik dedaunan sagu dan tangis perempuan, generasi tanpa tanah belajar menyebut hutan sebagai rumah. Negara berubah menjadi batas hidup dan mati.
Intan Jaya menjadi salah satu babak baru dari drama panjang ini. Pada 2020, lebih dari 8.000 warga sipil harus meninggalkan rumah mereka. Bentrok berkepanjangan antara TNI-Polri dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) menghancurkan desa-desa. Rumah dibakar, gereja berubah jadi tempat perlindungan (Komnas HAM, 2020).
Di Nduga, sejak akhir 2018, lebih dari 45.000 jiwa tercerai-berai. Mereka mengungsi usai operasi militer besar-besaran menyusul penembakan pekerja Trans Papua. Anak-anak kehilangan ruang kelas, ibu-ibu melahirkan di hutan tempat pengusian, dan banyak yang mati dalam diam. Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua mencatat, ini adalah salah satu pengungsian terbesar sejak reformasi (YKKMP, 2019).
Maybrat pun ikut menorehkan luka. Tahun 2021, setelah penyerangan pos Koramil di Kisor, lebih dari 3.000 warga lari ke hutan dan tempat-tempat tersembunyi. Mereka menghindari gelap bukan karena takut hewan liar, tetapi karena bayangan tentara lebih mengerikan (Jaringan Damai Papua, 2021).
Di Pegunungan Bintang, sejak 2023, dentuman meriam dan raungan pesawat tempur membuat langit robek. Warga kampung Oksibil dan sekitarnya memilih meninggalkan rumah menuju hutan, mencari keselamatan yang belum tentu ada (Suara Papua, 2023).
Cerita ini bukan hanya milik hari ini. Pada 2000, Wamena menjadi lautan bara dan jeritan. Ribuan warga mengungsi setelah kerusuhan besar. Pasar dibakar, kepala retak, dan rumah-rumah berubah jadi abu (Elsham Papua, 2001).
Lanny Jaya mencatat kisahnya tahun 2014. Setelah aparat ditembak, operasi militer membuat 1.000 orang lari ke hutan. Desa berubah menjadi kota mati. Tak ada suara tifa, hanya helikopter yang berputar-putar di langit (Papua Legal Aid Institute, 2014).
Yahukimo pun tak luput. Tahun 2022, Distrik Kiwirok menjadi tempat hujan peluru. Hampir 5.000 orang mengungsi. Tangisan bayi ditahan, karena isak bisa berarti kematian (Amnesty International, 2022).
Tahun 1996, Mimika dikepung ketegangan. Operasi militer pasca penyanderaan Mapenduma membuat lebih dari 3.000 warga lari ke hutan. Banyak yang tidak pernah kembali. TAPOL mencatat bahwa warga sipil menjadi korban utama operasi tersebut (TAPOL, 1996).
Sentani di awal 1990-an juga menjadi tempat berkumpulnya pengungsi dari wilayah pegunungan dan pesisir. Danau Sentani, yang dulu memantulkan langit biru, kini mencerminkan rasa takut dan kelaparan (Kompas Arsip, 1993).
Sota, perbatasan selatan Merauke, menjadi rumah darurat bagi pengungsi yang datang sejak gelombang 1980-an. Rumah-rumah berdinding pelepah sagu berdiri tak tetap. Mereka tidak tahu harus menunggu siapa atau pulang ke mana (Red Cross PNG, 2005).
Di Dogiyai, pasca kerusuhan 2023, ribuan warga mengungsi ke kampung-kampung tetangga dan hutan. Mereka bukan pelaku kekerasan, namun diperlakukan seperti buruan (Komnas HAM Papua, 2023).
Asmat tahun 2017, dihantam konflik antar kelompok dan campur tangan aparat. Dua ribu orang memilih hidup di rawa dan hutan. Nyanyian adat berubah menjadi bisikan ketakutan (BBC Indonesia, 2017).
Fakfak tahun 2003, pasca bentrokan sektarian, ratusan orang memilih keluar dari kota. Mereka tidak ingin diadili karena keyakinan atau warna kulit (ICG Report, 2003).
Jayapura tahun 2019 menyaksikan gelombang pengungsi politik setelah demonstrasi besar. Mahasiswa dan keluarganya menghilang dari asrama. Kota menjadi tempat sembunyi, bukan tempat belajar (The Guardian, 2019).
Biak tahun 1998. Tragedi Biak Berdarah menyisakan ratusan pengungsi yang melarikan diri ke Waropen. Mereka tidak ingin dikenal sebagai korban, tapi sejarah tak bisa dihapus (Biak Massacre Report, 1999).
Dari 1984 hingga 2024, lebih dari 100.000 jiwa telah mengungsi dari tanah kelahirannya sendiri. Ini bukan migrasi biasa, ini adalah pelarian dari peluru dan pengkhianatan negara. Data-data ini diperoleh dari berbagai sumber: Human Rights Watch, Komnas HAM, TAPOL, Amnesty International, Papua Legal Aid Institute, BBC Indonesia, The Guardian, Elsham, dan lembaga-lembaga lokal Papua.
Anak-anak di kamp pengungsian menggambar rumah dengan warna hitam. Bukan karena tak punya krayon, tapi karena tak tahu warna rumah mereka. Seorang perempuan tua memegang noken kosong, berharap hari ini bisa pulang dan membawa sesuatu. Tapi yang ia dapatkan hanya cerita-cerita sedih dari yang baru datang.
Di Papua, pengungsian bukan sekadar perpindahan fisik. Itu adalah pelarian spiritual. Mereka membawa serta bahasa, adat, ingatan, dan harapan. Sungai tahu cerita mereka. Batu-batu menyimpan doa yang tertahan. Pohon-pohon menjadi saksi bisu air mata yang tak pernah kering.
Papua menangis, tapi dunia hanya mendengar desir angin. Mereka melihat gambar-gambar di layar, tapi tak membaca makna di baliknya. Kampung-kampung yang dulu ramai, kini kembali jadi hutan.
Dan ketika seorang pengungsi di PNG berkata, “Saya lahir di tanah orang, mati pun mungkin di sini. Tapi roh saya, tetap pulang ke gunung”, kalimat itu menjadi puisi tak selesai. Sebab, sejarah pengungsian di Papua bukan tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang siapa yang dilupakan.
Penulis adalah Masyarakat yang tinggal di Dogiyai.