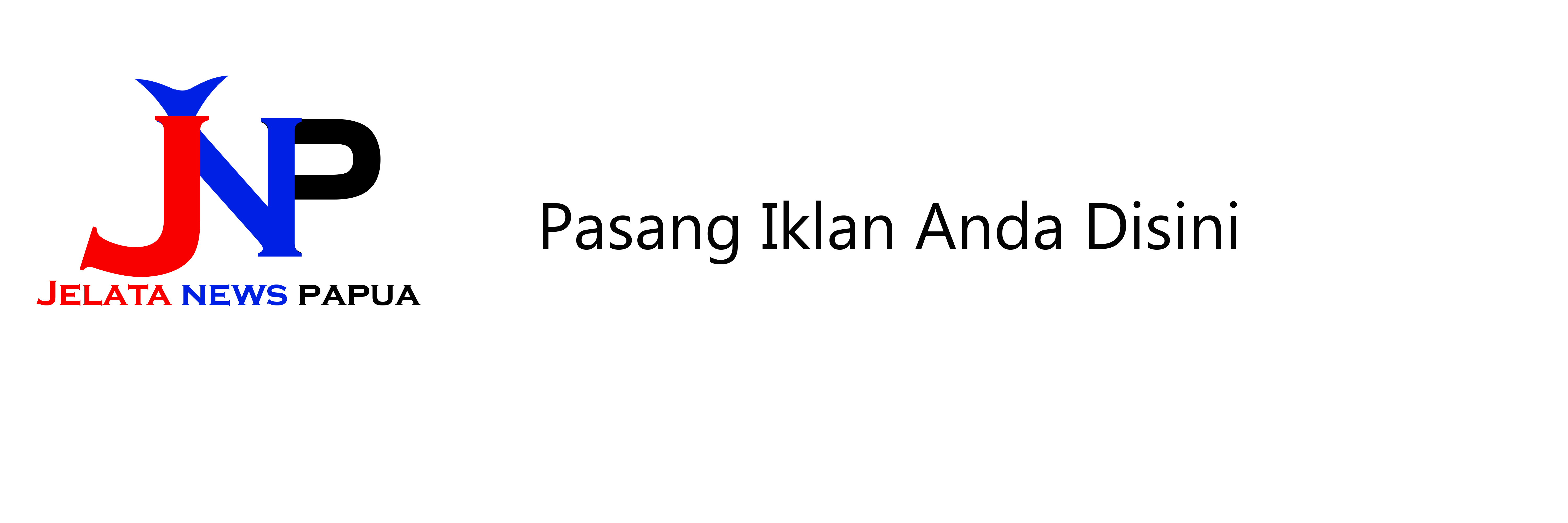Karya: Gusanncladote
Angin sore menyelinap lembut ke sela-sela dinding rumah papan di Maimani, membelai rambut Novita yang terurai pelan seperti hendak menyampaikan kabar dari langit. Di ruang tamu yang bersahaja, Yosapat duduk bersandar pada dinding, matanya menerawang ke luar jendela.
Di luar, Jalan Kenangan Toputo tampak lengang, seperti baru saja melepas pelayat terakhir dari sebuah kabar duka yang belum sempat usai. Udara membawa aroma tanah basah yang diselingi desir kesedihan.
Sudah lima nyawa pergi tanpa aba-aba. Mereka yang siangnya tersenyum di pasar, malamnya telah terbujur di rumah duka. Waktu tak lagi mengenal jeda.
“Mereka meninggal cepat sekali,” ucap Novita pelan, bibirnya nyaris tak bergerak. “Seperti senja yang tak sabar menjelma malam.”
Yosapat tak menjawab segera. Ia hanya menatap kosong ke dinding. “Ahk… demi, bikin kaget saja. Setiap malam seperti lomba duka, siapa berikutnya yang akan dipanggil.”
Jam tua di sudut rumah berdetak perlahan, tapi setiap tiknya terasa seperti bisikan kehilangan yang menjalar ke dalam dada.
“Yang buat saya takut,” bisik Yosapat, “yang meninggal itu bukan orang biasa. Kepala bidang, ketua gereja, ASN. Mereka dihormati di kampung ini.”
“Iya, saya dengar juga itu,” kata Novita, jemarinya menyentuh pelan ujung meja, seakan mencoba menggenggam ketenangan yang hilang. “Salah satu ASN di Distrik Kamuu Timur, siang masih keliling Pasar Moanemani, sorenya sudah pergi.”
“Kayaknya masih banyak lagi yang tidak tercatat,” lanjut Yosapat, suaranya melembut. “Teman-teman cerita, semua keracunan makanan. Makanan yang dijual bebas oleh pedagang migran di Pasar Moa.”
“Jangan-jangan kita juga pernah beli dari mereka…” lirih Novita, matanya menatap ke arah jendela yang mulai memantulkan bayangannya sendiri. Di balik kaca itu, seolah Tuhan bersembunyi dalam senyap.
Lampu bohlam di sudut rumah menyala remang, menyibak kegelapan yang perlahan menyelimuti rumah mereka. Di luar, suara lolongan anjing saling bersahutan, seperti alarm dari dunia yang kehilangan kendali.
“Kita harus lebih hati-hati, Yos,” ucap Novita pelan namun dalam. “Belanja makanan sekarang bukan sekadar urusan perut. Ini soal bertahan hidup.”
“Iyo, kita harus waspada,” jawab Yosapat. “Pasar bukan lagi tempat yang membawa pulang berkat. Bisa jadi, dia membawa maut.”
Malam merayap naik dari lembah, menyusuri batang pohon dan atap rumah, lalu masuk lewat celah-celah papan. Ia membawa dingin, membawa kecemasan.
Berita duka belum datang malam itu, tapi keduanya tahu, belum bukan berarti tidak. besok bisa saja ada lagi yang jatuh.
Di Dogiyai, kematian tak lagi mengetuk pintu. Ia masuk begitu saja, seperti kabut pagi yang tak butuh undangan. Ia datang dalam rupa nasi bungkus, lauk bersaus, atau air minum dalam botol plastik, rokok atau ayam hidup dan mati.
Pasar Moanemani yang dulu penuh tawa kini menjadi teka-teki yang menyeramkan. Setiap piring di sana kini menyimpan tanya: aman atau maut?
Warga berbisik di jalan, bahkan dalam doa. Siapa penjual itu? Dari mana mereka datang? Apa yang mereka bawa sebenarnya?
Tidak ada yang bisa menjawab pasti. Tapi yang jelas, tanah subur ini sedang menangis. Kehilangan demi kehilangan membuat tanah Lembah Kamu mulai retak di dalam diam.
Tuhan seperti terlalu diam, pikir Novita. Seolah membiarkan satu per satu anak-anak-Nya dipanggil dengan cara yang tak wajar.
“Apakah Tuhan sudah bosan melihat kami hidup?” gumamnya, nyaris tanpa suara.
Yosapat menggenggam tangan istrinya pelan. Ia tidak tahu jawaban, tapi genggaman itu setidaknya membuat malam terasa sedikit lebih hangat.
Rumah-rumah lain di Maimani pun ikut terdiam. Tak ada tawa anak-anak, tak ada suara musik, hanya desah nafas dari dinding-dinding kayu yang mulai letih menyimpan cerita sedih.
Besok pagi, mentari mungkin akan terbit lagi, tapi belum tentu semua wajah akan menyambutnya. Mungkin ada lagi satu rumah yang menangis.
Di Pegunungan Mapiha, awan-awan menggantung berat, seolah ikut memikul duka yang belum juga reda.
“Kalau ini ujian, semoga Tuhan beri kita kekuatan melewatinya,” bisik Yosapat, matanya tak lepas dari nyala lampu kecil yang bergoyang pelan diterpa angin.
Novita menunduk, menyandarkan kepala di bahu suaminya. Di luar, malam masih panjang, tapi hati mereka telah siap menjaga satu sama lain.
Mereka hanya ingin hidup sederhana, dalam damai yang tenang. Di tanah kelahiran yang mereka cintai.
Tapi untuk sekarang, mereka hanya bisa berdoa. Agar besok tak ada lagi senja yang terlalu cepat. Agar Dogiyai pulih. Agar Lembah Kamuu kembali dalam pelukan damainya.
Catatan Akhir:
Cerpen: “Senja yang Terlalu Cepat di Lembah Kamuu, Dogiyai” adalah karya fiksi yang ditulis berdasarkan peristiwa nyata yang terjadi dalam bulan Juni dan Juli di Lembah Kamuu, Dogiyai, Papua Tengah. Kisah ini mencoba menangkap suasana batin masyarakat yang dihantui kabar kematian mendadak, diduga akibat keracunan makanan dari pasar lokal Moanemani.
(Lembah Kamuu, Dogiyai, 03 Juni 2025)